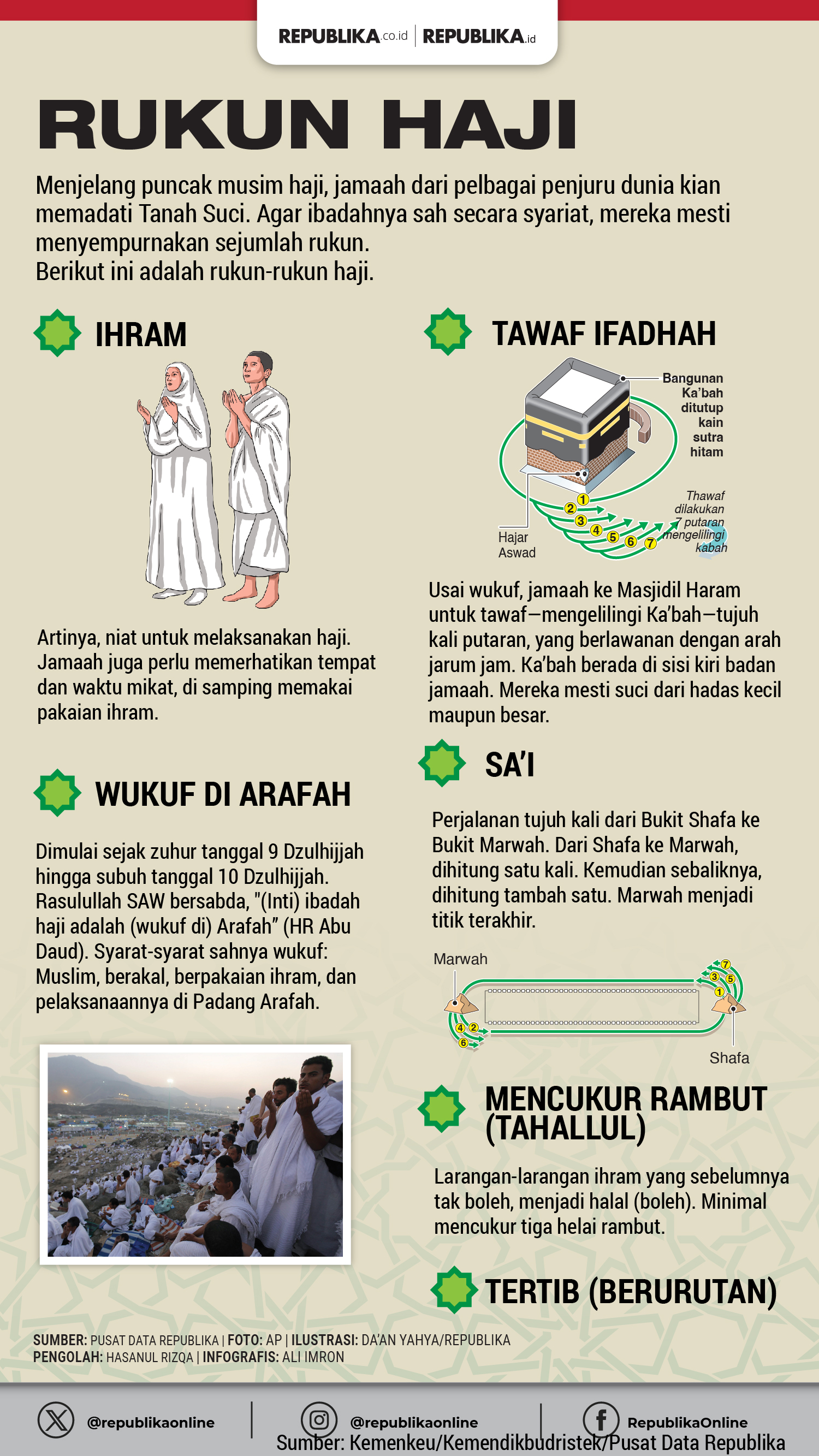REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibadah haji mengandung banyak pelajaran dan hikmah. Salah satunya adalah tentang terbatasnya rasionalitas manusia. Sejak awal sejarah ibadah haji, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di tengah padang pasir Makkah yang tidak berpenduduk, rasionalitas kita mulai diuji.
Rasio manusia umumnya akan menggugat tentang “ketegaan” Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan bayinya hanya berdua di tengah padang pasir tandus. Namun, bagi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar karena keimanan dan ketakwaan mereka yang kukuh dan mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah, maka mereka taat, berdoa, dan yakin bahwa Allah akan menolong mereka (QS 14: 37, HR Bukhari: 3113).
Kita sudah mengetahui bahwa Allah memang kemudian menolong dan mengurus Siti Hajar dan bayi Ismail dengan cara-Nya yang juga tidak terbayangkan oleh rasionalitas manusia (lihat HR Bukhari: 3113).
Saat Nabi Ibrahim juga mematuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail, rasionalitas kemanusiaan kita juga umumnya akan mempertanyakan. Mengapa Nabi Ibrahim tega untuk menyembelih putranya tercinta yang sudah berpuluh tahun ditunggu kelahirannya?
Namun sekali lagi, rasionalitas Nabi Ibrahim dan Ismail yang ridha dengan perintah tersebut (QS 37:102), sudah melampaui rasionalitas manusia umumnya. Rasionalitas beliau berdua sudah dituntun oleh kebeningan hati serta cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang murni.
Pengalaman pribadi kami dan sejumlah rekan saat berhaji, serta berbagai kisah berhaji sejumlah ulama yang kami baca, menyiratkan bahwa ibadah haji punya beragam lapisan makna.
Fenomenanya kadang sulit dijelaskan dengan rasionalitas umumnya manusia. Contohnya, ada orang yang secara finasial dan kondisi fisik sangat baik, tapi tidak pernah berkesempatan untuk berhaji.