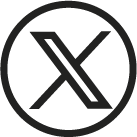REPUBLIKA.CO.ID, Pada 1874, Belanda juga memberlakukan kebijakan yang menyulitkan, yakni jamaah haji diharuskan memiliki tiket pergi-pulang.
Ketentuan ini mungkin menguntungkan karena menunjang sistem monopoli bagi perusahaan pengangkut haji.
Sedangkan bagi pemerintah Hindia Belanda, ketentuan ini memudahkan kontrol mereka terhadap jamaah haji.
Dengan ketentuan tersebut, jamaah haji hanya diizinkan berangkat di sejumlah pelabuhan yang telah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Mereka yang berangkat dari Hindia Belanda membawa pas perjalanan ke Makkah yang ditandatangani oleh pegawai pangreh Praja dengan terlebih dahulu pergi ke sebuah pelabuhan embarkasi jamaah. Pas tersebut harus diserahkan untuk ditandatangani oleh seorang penguasa pelabuhan.
Setibanya di Pelabuhan Jeddah, terlebih dulu jamaah menghadap konsulat Belanda dengan menukarkan pas jalannya dengan pas izin tinggal selama musim haji. Setibanya kembali di Tanah Air, pas itu sekali lagi harus ditandatangani oleh penguasa-penguasa Belanda.
Bahkan, pas perjalanan model tahun 1884 ini, tak hanya memuat keterangan tentang jenis kelamin, umur, dan tinggi badan, tetapi juga keterangan mengenai bentuk hidung, mulut, dan dagu, serta tentang apakah si pemilik pas berkumis, jenggot, atau lainnya.
Pulau Onrust
Pengawasan terhadap jamaah haji semakin menjadi-jadi ketika Belanda mengeluarkan aturan baru untuk mengumpulkan para calon haji dan mereka yang selesai berhaji di sebuah pulau bernama Onrust.
"Nama 'Onrust' diambil dari bahasa Belanda yang artinya 'Tidak Pernah Beristirahat' atau dalam bahasa Inggrisnya 'Unrest'," ujar wartawan senior sekaligus pemerhati sejarah Betawi, Alwi Shahab.
Sebelum difungsikan sebagai tempat embarkasi dan karantina haji pada 1911 hingga 1933, pulau yang terletak di kawasan Kepulauan Seribu ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Belanda. "Di pulau ini para tentara Belanda beraktivitas bongkar muat logistik perang," kata pria yang akrab disapa Abah Alwi ini.