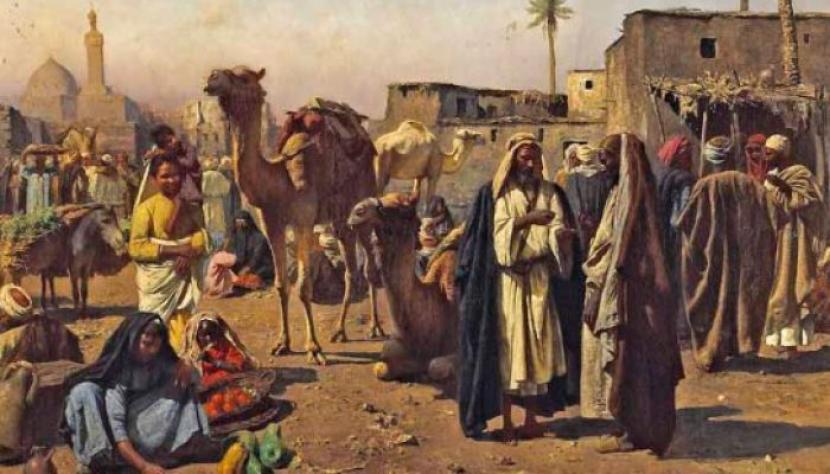Dalam sejarah umat Islam di Indonesia dijumpai pula tokoh-tokoh ulama yang berkepribadian mulia dan selalu konsisten dalam berprinsip. Pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang muncul pahlawan nasional bernama KH Zainal Musthofa (1901-1944), pemimpin Pesantren Sukamanah, Jawa Barat.
Menurut KH Abdul Aziz Masyhuri (1942-2017) dari Denanyar, Jombang, di dalam karyanya berjudul 99 Kiai Kharismatik Indonesia, pada awal tahun 1940-an KH Zainal Musthofa menyerukan perlawanan kepada pemerintah kolonial. Upaya Belanda untuk menjinakkan sikap beliau tidak pernah berhasil sehingga beliau ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis pada tahun 1941.
Meskipun beliau dibebaskan penjajah Jepang pada 1942, ternyata pembebasannya itu tidak mengubah penentangannya terhadap penjajahan. Ajakan Jepang yang membujuknya agar bergabung dalam pemerintahan ditolaknya mentah-mentah.
Saat itu Jepang memaksa para pemuka agama Islam supaya bersedia menggunakan ayat-ayat suci al-Qur’an dan juga otoritas mereka untuk mengelabui rakyat demi mendukung Jepang. Apabila mereka menolak, maka ancaman hukuman berat akan ditimpakan kepada mereka.
Penjajah Jepang berkali-kali gagal melunakkan pendirian KH Zainal Musthofa. Pada 24 Februari 1944 Jepang mulai mengirimkan pasukan (yang sebagiannya justru terdiri dari warga pribumi) untuk menyerang Pesantren Sukamanah. Dalam pertempuran tidak seimbang itu banyak pejuang Muslim berguguran dan KH Zainal Musthofa kemudian ditangkap.
Pada akhir Maret 1944 beliau dibebaskan Jepang dengan harapan mau membantu Jepang. Namun dalam pidato penyambutannya di Pesantren Sukamanah, ternyata beliau tetap menentang Jepang dan tidak mau melakukan seikeirei (pemberian hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo), karena perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak akidah tauhid serta mengalihkan arah kiblat.
Beliau menyebut orang Jepang sebagai musyrik dan mengecam keras pengerahan romusha (kerja paksa) oleh penjajah Jepang. Kemarahan Jepang pun memuncak sehingga beliau syahid setelah dihukum mati penjajah pada 25 Oktober 1944.
Keteguhan sikap dicontohkan pula oleh KH Asnawi (1861-1959) dari Kudus, Jawa Tengah, yang sangat menentang kolonialisme sehingga beliau dipenjara oleh penjajah Belanda pada 1918 selama tiga tahun. Karena beliau merupakan kiai berpengaruh yang memiliki kharisma tinggi, maka Belanda menawarkan jabatan sebagai hakim agama di Kudus.
Meskipun beliau menyambut kedatangan Van Der Plas dengan ramah, namun dengan tegas beliau menolak menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Dalam pandangannya, aktivitas amar makruf nahi munkar memerlukan kebebasan dan independensi sehingga akan sulit bagi beliau untuk menjalankan dakwah apabila menjadi pejabat pemerintah. Apalagi kegiatan dakwah itu harus sering ditujukan kepada penjajah.
Keputusan semacam itulah yang diambil juga oleh KH Moenawar Chalil, penulis buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw. Beliau pada pertengahan tahun 1952 menolak tawaran Presiden Soekarno untuk posisi tinggi di Jakarta dan tidak mau menduduki posisi sebagai Menteri Agama yang ditawarkan kepadanya oleh kabinet koalisi Partai Nasionalis Indonesia (PNI) - Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
Menurutnya, apabila dirinya menjadi pejabat pemerintah pusat di ibukota, maka hal itu akan memaksanya untuk menghentikan sikap kritisnya kepada pemerintah karena integritas moral lebih berharga dan terhormat daripada jabatan tinggi di Jakarta.
Di samping itu, beliau ingin memusatkan seluruh tenaga dan waktunya untuk kegiatan berdakwah dan menulis setelah sempat terhenti sejak tahun 1941. Demikian dituturkan Thoha Hamim dalam karyanya Moenawar Chalil’s Reformist Thought: A Study of an Indonesian Religious Scholar (1908-1961).
Bagi seorang ulama sejati, jabatan formal tidak perlu dikejar maupun dipertahankan mati-matian. Sebab konsistensi pengamalan ajaran Islam dan kesungguhan dalam perjuangan dakwah jauh lebih utama dari sekedar mendapatkan penghargaan dari penguasa.
Namun keberadaan dirinya sebagai ulama seringkali dalam kondisi terkungkung dan tidak bisa bersikap kritis menyampaikan kebenaran. Kiai Moenawar senantiasa berprinsip bahwa kebenaran harus disampaikan kepada siapapun, termasuk kepada penguasa, meski kebenaran itu terasa pahit.
Sejarah mencatat KH Moenawar Chalil sangat berpantang dan tidak sudi merendahkan martabatnya di depan penguasa politik hanya demi mendapatkan jabatan. Kehormatannya sebagai cendekiawan tidak layak digadaikan begitu saja dengan harga amat murah.
Meskipun demikian, pemaparan di atas bukan berarti bahwa ulama dilarang untuk menjalin hubungan kerjasama dengan penyelenggara pemerintahan (umara). Hal utama yang hendak ditekankan di sini ialah mengenai kewajiban ulama agar senantiasa mempertahankan independensinya tatkala bergandengan tangan dengan pemegang kekuasaan politik.
Pada dasarnya, kewibawaan ulama sama sekali tidak akan berkurang dimanapun dirinya berada, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, sehingga sangatlah tidak etis apabila ada sekelompok masyarakat yang mencemooh, mengolok-olok, dan berkomentar negatif pada ulama yang tidak menempati posisi struktural di lembaga resmi pemerintah.
Seluruh ulama, tanpa melihat warna baju golongannya, seharusnya saling bahu membahu dalam membina dan membentengi kaum Muslimin sambil tetap menjunjung toleransi dan kerukunan terhadap sesama umat Islam maupun penganut agama lainnya.