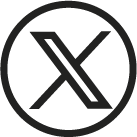REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah derasnya arus informasi digital, hoaks dan disinformasi menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Jauh sebelum era media sosial, Tan Malaka sudah resah terhadap cara berpikir irasional yang ia sebut sebagai logika mistika.
Untuk melawannya, ia menulis karya monumental Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) pada 1942–1943. Kini, gagasannya justru makin relevan sebagai senjata menghadapi hoaks dan polarisasi di era post-truth.
Madilog bukan dogma baru, melainkan alat berpikir kritis. Tan Malaka merancangnya sebagai “software” bagi bangsa yang hendak merdeka 100 persen, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara mental. Menurutnya, mustahil bangsa merdeka jika masih tunduk pada takhayul, mitos, atau propaganda tanpa dasar.
Isi Madilog dapat dipahami sebagai tiga jurus utama:
1. Materialisme: Cek Fakta Dulu, Bro!
Materialisme menuntut bukti nyata sebelum percaya pada klaim apa pun. Dalam konteks hari ini, ia identik dengan fact-checking. Saat pesan berantai di WhatsApp mengklaim bahwa “rebusan bawang putih bisa sembuhkan segala penyakit”, cara berpikir materialis langsung bertanya: mana bukti ilmiahnya?.
2. Dialektika: Lihat dari Dua Sisi, Jangan Baperan
Media sosial sering menciptakan echo chamber yang memperkuat polarisasi. Dialektika mengajarkan bahwa kebenaran justru lahir dari pertentangan pandangan. Dengan cara ini, masyarakat terlatih untuk berdialog, bukan saling blokir atau cancel.
3. Logika: Polisi Sesat Pikir
Di era banjir opini sekarang ini juga banyak argumen sesat (fallacies) digunakan untuk menggiring opini publik. Nah, logika berfungsi membedah argumen, menemukan cacat nalar, dan menjaga agar kesimpulan tetap runut. Ia ibarat vaksin terhadap virus propaganda.
Hari ini, hoaks menyebar bukan lagi lewat gosip di warung kopi, melainkan dalam hitungan detik melalui media sosial. “Logika mistika” berganti baju menjadi mentalitas post-truth: lebih percaya pada emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta objektif.
Di sinilah Madilog menjadi senjata pamungkas. Ia berfungsi sebagai “antivirus orisinal buatan Bapak Republik” untuk melawan virus hoaks. Dengan materialisme kita terlatih bertanya, “Apa buktinya?”; dengan dialektika kita belajar menimbang dari berbagai sisi; dan dengan logika kita mampu menolak narasi menyesatkan.
Selama Orde Baru, nama Tan Malaka dan Madilog dipinggirkan karena dianggap berbahaya. Namun, pasca-Reformasi, generasi baru kembali menemukan relevansi pemikirannya.
Mengkaji Madilog bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan tindakan politik intelektual: merebut kembali warisan berpikir kritis yang nyaris dihapus, sekaligus memperlengkapi diri menghadapi hoaks dan propaganda di abad ke-21.
Seperti pernah ia tulis sebelum dieksekusi, “Ingatlah! Bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi.” Gagasan Madilog membuktikan ramalan itu, terus hidup dan relevan melawan kebodohan, polarisasi, dan hoaks hingga hari ini.