Ketokohan Syekh Hamzah Fansuri berkaitan dengan ajaran Wujudiyah. Namun, ada beberapa kesalahpahaman yang mesti diluruskan terlebih dahulu. Abdul Hadi WM (1995) menjelaskan, jalan tasawuf yang disebarluaskan Syekh Hamzah Fansuri dipengaruhi gagasan-gagasan dari Arab dan Persia sebelum abad ke-16.
Figur-figur terkemukanya antara lain Bayazid Bisthami, Mansur al-Hallaj, Fariduddin ‘Attar, Syekh Junaid al-Baghdadi, Ahmad Ghazali, Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, Mahmud Shabistari, dan ‘Iraqi. Di antara nama-nama itu, ‘Iraqi (wafat 1289) sering dikutip Hamzah Fansuri untuk menguraikan pemikirannya tentang tasawuf. Sufi kelahiran Kamajan, Persia, itu merupakan pengarang Lama’at dan pernah berguru pada Sadruddin Qunawi (wafat 1274)—hidup sezaman dengan Rumi.
Menurut Abdul Hadi, Qunawi-lah yang pertama-tama mengemukakan istilah wahdatul wujud berdasakan penelaahannya atas karya-karya Ibnu ‘Arabi. Istilah itu untuk menyatakan, keesaan Tuhan tidak bertentangan dengan gagasan tentang penampakan pengetahuan-Nya yang berbagai-bagai di alam fenomena (‘alam al-khalq).
Tuhan sebagai Zat Mutlak satu-satunya di dalam keesaan-Nya memang tanpa sekutu dan bandingan, dan karenanya Tuhan adalah transenden (tanzih). Namun, karena Dia menampakkan wajah-Nya serta ayat-ayat-Nya di seluruh alam semesta dan di dalam diri manusia, Dia memiliki kehadiran spiritual di alam kejadian (Abdul Hadi, 1995: 21-22).
Argumen wahdatul wujud dapat diperoleh dari pemaknaan atas dua dari 99 asma al-husna, yakni Yang Zahir dan Yang Batin. Selain itu, di dalam Alquran surah Qaf ayat ke-16 juga ditegaskan bahwa “Kami lebih dekat kepadanya (manusia) daripada urat lehernya.”
Di samping transenden, Dia juga immanen (tashbih). Asas penampakan Tuhan melalui pengetahuan-Nya atau Wujud-Nya ialah Cinta (‘isyq). Oleh karena itu, terang Abdul Hadi, bila kaum wujudiyah berbicara tentang ‘isyq, maka yang dimaksudkannya adalah Wujud Tuhan, yang tidak lain adalah Sifat-sifat-Nya yang tampak melalui segala pekerjaan-Nya.
Salik dengan pemahaman semisal itu kerap mengutip hadits qudsi, “Aku perbendaharaan tersembunyi, Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta dan dengan demikian Aku dikenal.” Untuk memahaminya, perhatikanlah kalimat “Bismillahirrahmaanirrahiim.”
Di sana, terdapat dua macam Cinta, yakni rahman dan rahim. Keduanya berasal dari akar kata yang sama, rahma. Namun, yang pertama bersifat esensial, sedangkan yang kedua bersifat wajib. Rahman berarti, cinta Tuhan berlaku atas segala ciptaan-Nya. Sementara itu, Rahim merupakan rahman-Nya yang wajib. Rahim atau cinta yang wajib itu mesti dilimpahkan kepada orang-orang tertentu yang mencinta-Nya dengan penuh kesungguhan, yakni mereka yang beriman dan beramal saleh.
Hamzah Fansuri dan Wujudiyah
Ajaran Wujudiyah itu tergambar dalam banyak syair Hamzah Fansuri. Abdul Hadi menyebutkan beberapa di antaranya. “Tuhan kita yang bernama qadim/Pada sekalian makhluq terlalu karim/Tandanya qadir lagi hakim/Menjadikan alam dari Al-Rahman Al-Rahim// Rahman itulah yang bernama Sifat/Tiada bercerai dengan kunhi Zat/Di sana perhimpunan sekalian ibarat/Itulah hakikat yang bernama ma’lumat.”
Wujudiyah yang dikembangkan Hamzah Fansuri bukanlah seperti Martabat Tujuh. Abdul Hadi menekankan, syekh asal Barus itu seperti halnya para wali di Pulau Jawa pada abad ke-16—sebut saja, Sunan Bonang atau Sunan Kalijaga. Persamaannya, tidak pernah menjadi penganjur aliran Martabat Tujuh.
Aliran itu sendiri merupakan perkembangan selanjutnya dari Wujudiyah yang telah dipengaruhi sinkretisme dengan kebudayaan India. Pengagas pertama Martabat Tujuh bernama Mohamad Fadlullah al-Burhanpuri (wafat 1620). Ketika ajarannya diasaskan, berbagai gerakan sinkretis berkembang di India, terutama pada masa Sultan Akbar dan Dara Sukoh. Di Nusantara, praktik-praktik para penganut aliran Martabat Tujuh kerap mencampurbaurkan keyakinan dengan tradisi India. Misalnya, praktik yoga di dalam amalan zikir.
Justru, Hamzah Fansuri bersikap kritis terhadap Martabat Tujuh. Hal itu tampak dari catatan seorang laksamana Prancis, Beauleu, yang berkunjung ke Aceh. Beauleu menyebut, Sultan Aceh saat itu berang akan adanya seorang alim yang menegurnya. Saat itu, demikian cerita tamu asal Eropa tersebut, sang sultan sedang menyiapkan suatu upacara meditasi menyambut datangnya bulan purnama.
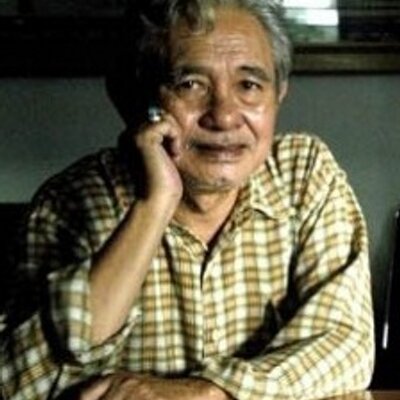
Prof Abdul Hadi WM (sumber: Twitter @abdulhadiwm)
Abdul Hadi mengutip pendapat orientalis Braginsky yang memastikan, orang alim tadi adalah Syekh Hamzah Fansuri. Pada masa transisi dari abad ke-16 menuju 17, Aceh sedang berada dalam puncak kejayaan di Sumatra. Namun, krisis politik kerap menerpa istana, sehingga meluputkan elite penguasa dari ajaran Islam yang benar.
Abdul Hadi menukas, pada era itu, tasawuf digemari kalangan atas, tetapi dalam pelaksanaannya kerap bercampur dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan hakikat sufi. Sebut saja, praktik yoga tadi yang sesungguhnya tradisi India. Dalam pemahaman agama Hindu, pelaku membayangkan Tuhan sebagai rahasia yang berada di bagian tertentu tubuh manusia, semisal ubun-ubun.
Hamzah Fansuri mengkritik sinkretisme demikian antara lain dalam Asrar al’Arifin: “[…] jangan bermaqam di ubun-ubun atau di pucuk hidung atau di antara kening atau di dalam jantung; sekalian itu hijab kepada Dzat-Nya.” Akhirnya, sang salik menegaskan jalan tasawuf hanya dapat dicapai melalui peniadaan “diri yang rendah”, untuk kemudian menyadari Sifat-sifat-Nya. “Ketahui olehmu hai anak dagang/Rupamu itu seperti bayang-bayang/Menafikan diri jangan kau sayang/Supaya dapat kepada Huwa (Dia) kau datang.”



